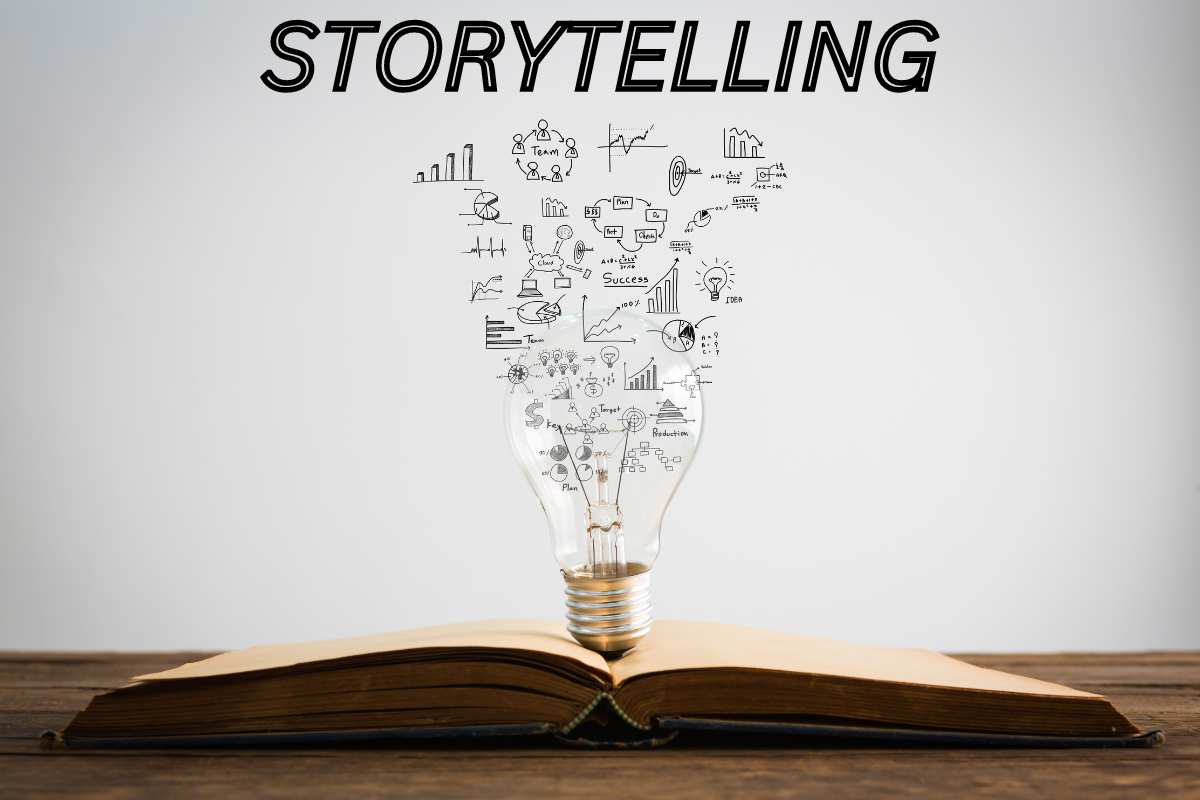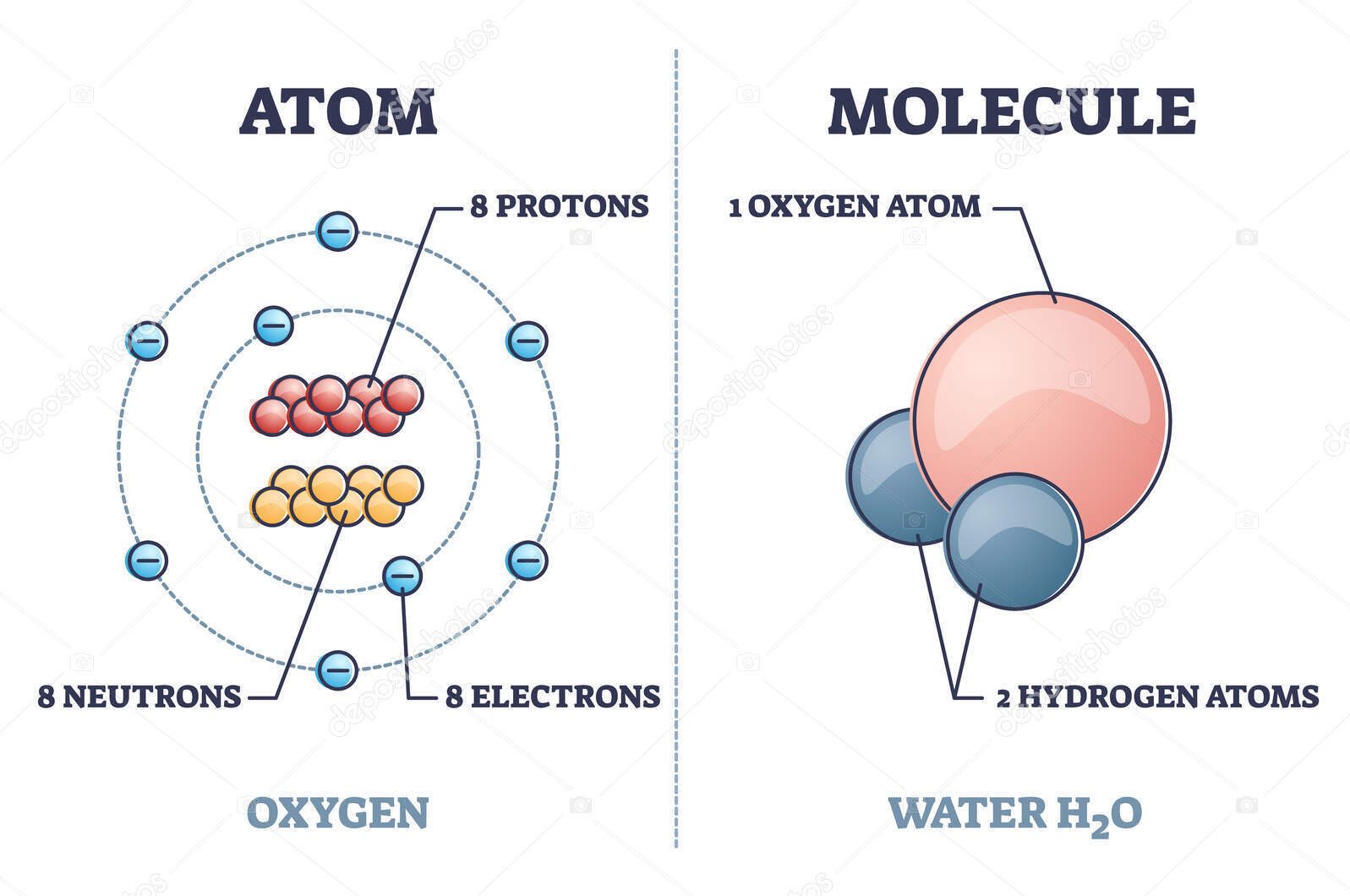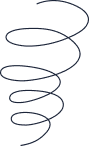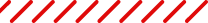Jakarta, inca.ac.id – Bayangkan sebuah pagi di pelosok desa, suara ayam bersahutan, embun masih menempel di daun jagung, dan seorang penyuluh muda berdiri di tengah sawah, membawa secarik kertas berisi informasi tentang pupuk hayati terbaru. Itulah wajah nyata penyuluhan pertanian: ilmu pengetahuan yang berjalan kaki, menjumpai petani dari dekat.
Penyuluhan pertanian bukan hanya agenda pemerintah atau formalitas proyek. Ia adalah instrumen vital untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada petani secara aplikatif. Sebab, seberapa canggih pun hasil riset pertanian, jika tak sampai ke tangan petani, maka hanya akan jadi angka di jurnal ilmiah.
Penyuluh ibarat “translator” ilmu. Mereka menjembatani bahasa akademik yang kaku dengan realitas lapangan yang dinamis. Mulai dari metode tanam yang tepat guna, pengelolaan hama terpadu, hingga literasi pemasaran hasil tani—semua itu dibawa langsung ke kebun, ladang, dan sawah, bukan hanya dibicarakan dalam ruang seminar.
Menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), penyuluhan adalah kunci dalam menyukseskan regenerasi pertanian. Tanpa itu, ada kesenjangan antara pengetahuan dengan praktik. Banyak petani muda pun merasa asing dengan inovasi karena tidak adanya media pembelajaran yang membumi.
Bahkan, dalam beberapa kasus, penyuluhan telah menjadi penyelamat di masa krisis. Seorang petani di Bojonegoro, misalnya, mampu mempertahankan hasil panen padinya saat musim kemarau 2022 hanya karena mengikuti program penyuluhan tentang pengairan alternatif menggunakan metode sumur resapan.
Dari kisah-kisah itulah, kita paham, penyuluhan bukan sekadar agenda tahunan. Ia adalah denyut kehidupan pertanian itu sendiri.
Peran Strategis Penyuluh: Dari Penggerak Lapangan Hingga Konsultan Lokal

Tak banyak profesi yang menuntut kombinasi ilmu, ketulusan, dan adaptasi sekuat penyuluh pertanian. Mereka bukan hanya guru, tapi juga kawan dialog, pemecah masalah, bahkan sering jadi tempat curhat para petani yang bingung harus mulai dari mana.
Penyuluh pertanian harus fleksibel: pagi bisa jadi moderator diskusi kelompok tani, siang memberi pelatihan budidaya hortikultura, sore menyusun laporan evaluasi ke dinas, dan malam masih menjawab pertanyaan petani lewat WhatsApp tentang hama ulat grayak. Mereka adalah garda depan yang menjembatani kebijakan dengan realita.
Uniknya, penyuluh juga berperan sebagai konsultan lokal yang paling dipercaya. Kenapa? Karena mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga mendengar. Contoh nyata datang dari seorang penyuluh di Kulon Progo yang mengembangkan varietas lokal melon kuning setelah mendengar keluhan petani tentang harga pasar yang tidak stabil. Melalui riset kecil dan uji coba bersama petani, varietas baru itu akhirnya sukses menembus pasar ritel nasional.
Namun tantangan mereka tidak sedikit. Kurangnya fasilitas transportasi, keterbatasan internet di desa, dan minimnya insentif sering membuat peran penyuluh kurang diapresiasi. Padahal, mereka adalah pion penting dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.
Mereka bukan robot. Mereka manusia yang penuh dedikasi, dan dalam sunyi mereka bekerja, menyalakan harapan di ladang-ladang negeri.
Penyuluhan Era Baru — Digitalisasi dan Generasi Petani Milenial
Dulu, penyuluhan identik dengan pertemuan di balai desa dan selebaran. Sekarang? Masuk ke dunia konten video, grup WA petani, hingga diskusi daring lewat Zoom. Digitalisasi bukan ancaman, tapi peluang baru bagi penyuluhan untuk menyentuh generasi muda.
Generasi milenial dan Gen Z yang melek teknologi justru tertarik saat pendekatan penyuluhan lebih visual dan interaktif. Coba saja cek akun TikTok milik beberapa penyuluh muda di Sulawesi Selatan—mereka mengedukasi soal pola tanam jagung, cara membuat pupuk kompos dari limbah dapur, hingga tips ekspor hasil panen.
Penyuluhan tak lagi monoton. Ia bisa hadir dalam bentuk podcast, thread X (dulu Twitter), sampai vlog YouTube yang membahas teknik irigasi tetes. Pendekatan ini terbukti efektif. Di Lampung, produktivitas lahan petani milenial meningkat 23% dalam dua musim tanam setelah mengikuti kelas penyuluhan berbasis daring.
Namun demikian, digitalisasi juga membawa tantangan. Tidak semua wilayah punya akses internet stabil, dan tidak semua petani nyaman dengan teknologi. Maka, model hybrid antara penyuluhan tatap muka dan digital harus dirancang dengan cermat agar inklusif.
Transformasi ini menunjukkan bahwa penyuluhan bukan entitas statis. Ia berevolusi bersama zaman, dan mampu menjadi inspirasi baru bagi anak muda yang ingin kembali ke sawah bukan karena terpaksa, tapi karena bangga.
Program Pemerintah dan Tantangan Implementasi di Lapangan
Berbagai program penyuluhan telah diluncurkan pemerintah, mulai dari Program YESS (Youth Entrepreneurship and Employment Support Services) yang menyasar petani muda, hingga Petani Andalan yang menyinergikan penyuluh dengan koperasi tani. Namun, realitas implementasi sering kali berbicara lain.
Banyak penyuluh mengeluhkan keterlambatan dana operasional, distribusi modul yang belum merata, hingga birokrasi berbelit saat pelaporan. Di sisi lain, ada ketimpangan jumlah penyuluh dan wilayah tugas. Di NTT, seorang penyuluh bisa menangani 5 desa sekaligus, padahal idealnya 1 desa ditangani oleh 1 orang.
Tantangan lain adalah pendekatan yang terlalu seragam. Padahal, karakter petani di Jawa Barat yang intensif hortikultura tentu berbeda dengan petani lahan kering di Nusa Tenggara. Ini menuntut penyuluh untuk mampu melakukan adaptasi lokal dan membaca konteks wilayah.
Namun, bukan berarti tak ada solusi. Di beberapa kabupaten, model penyuluhan berbasis komunitas terbukti lebih efektif. Petani didorong aktif menyusun agenda dan konten penyuluhan bersama, sehingga materi terasa lebih membumi. Konsep ini mirip dengan “agro-literacy circle” yang diterapkan di Filipina dan Vietnam.
Penyuluhan harus terus dikawal. Tidak hanya oleh dinas, tapi juga oleh media, masyarakat sipil, bahkan dunia kampus. Tanpa pengawalan publik, penyuluhan berisiko tenggelam dalam tumpukan administrasi, padahal jantungnya adalah pelayanan langsung ke petani.
Menyalakan Harapan: Masa Depan Penyuluhan di Tangan Kolaborasi
Jika penyuluhan pertanian adalah jembatan antara riset dan petani, maka kolaborasi adalah tiangnya. Masa depan penyuluhan harus dibangun bersama—bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga akademisi, swasta, hingga content creator pertanian.
Beberapa startup agritech mulai melirik peran penyuluh sebagai partner strategis, bukan sekadar user. Mereka menyediakan dashboard informasi cuaca, harga pasar, dan konsultasi hama yang bisa diakses oleh penyuluh untuk disampaikan ke petani. Di sisi lain, kampus pertanian mulai menjadikan penyuluhan sebagai bagian dari kurikulum, lengkap dengan praktik lapangan.
Tak kalah menarik, penyuluhan berbasis peer-to-peer juga makin populer. Petani senior melatih petani muda dengan difasilitasi penyuluh. Pendekatan ini bukan hanya efisien, tapi juga membangun rasa percaya antarpetani. Sebab, seringkali, sesama petani lebih mudah memahami bahasa satu sama lain.
Ada pula potensi besar dari pelibatan perempuan dalam penyuluhan. Di banyak desa, perempuan berperan penting dalam pengelolaan rumah tangga tani, tetapi sering tak dilibatkan dalam sesi penyuluhan. Mengubah ini bisa jadi titik balik dalam mengangkat produktivitas sekaligus kesetaraan.
Akhirnya, penyuluhan bukan sekadar transmisi ilmu. Ia adalah proses pemanusiaan pertanian. Dan selama ada semangat kolaborasi, harapan itu akan terus menyala, dari ladang ke ladang, dari generasi ke generasi.
Baca Juga Konten dengan Artikel Terkait Tentang: Pengetahuan
Baca Juga Artikel Dari: Bisnis Pertambangan: Ilmu Penting bagi Mahasiswa Industri Energi
#Penyuluhan #Penyuluhan Pertanian #Pertanian #Pertanian Penyuluhan